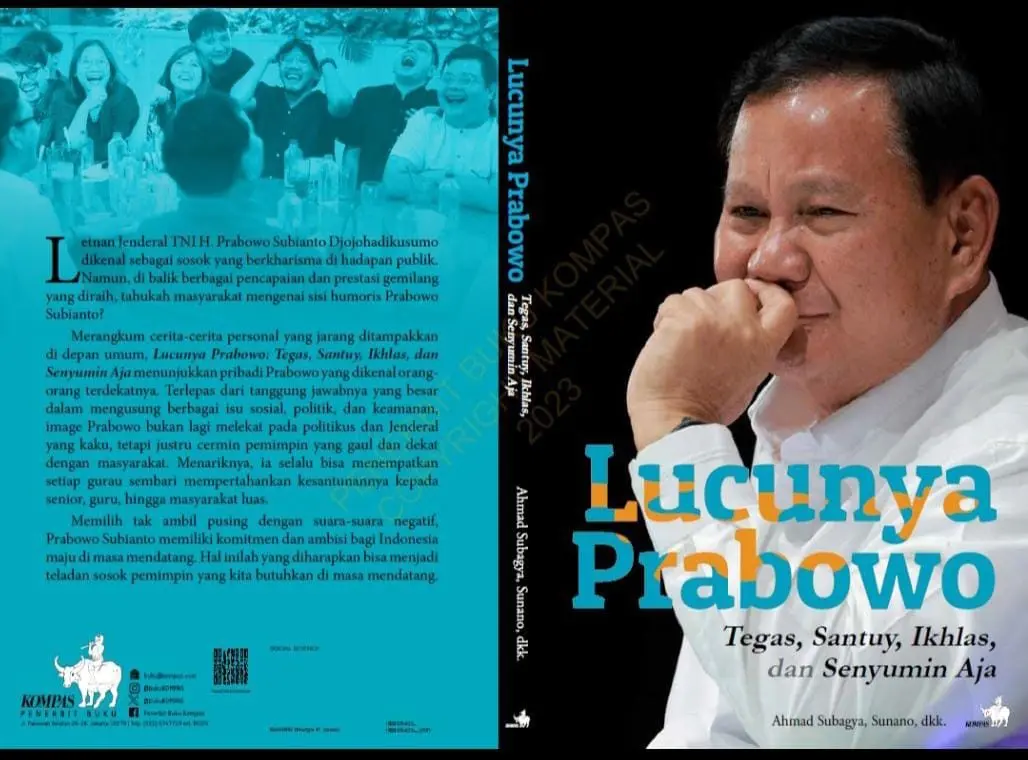Oleh : Bachtiar S. Malawat
Aphromdite Pandemos perempuan yang diabadikan dalam cerita masyarakat Athena Yunani kuno kala itu sebagai dewi kenikmatan seksual dalam budaya prostitusi klasik. Prostitusi sendiri kali pertama lahir pada 2400 sebagai pekerjaan tertua di muka bumi dimana para perempuan dibagi dalam tiga kelas.
Kelas pertama adalah perempuan yang hanya diizinkan melakukan ritual hubungan seks dengan para pria, sementara kelas kedua hanya melayani pengunjung dan kelas ketiga hanya untuk orang-ornag yang tinggal di dalam kuil tersebut.
Prostitusi dianggap sebagai pekerjaan spritual dalam konteks memuaskan nafsu laki-laki untuk cinta dan kasih sayangnya terhadap dewi kehidupan yang diyakini masyarakat yunani kuno kala itu, prostitusi di anggap sebagai pekerjaan mulia yang menghubungkan diri mereka kepada dewa dan dewi.
Pekerjaan ini melibatkan perempuan secara sukarela degan keyakinan bahwa diri mereka dijual dan ditukar dengan apa yang diberikan laki-laki untuk semata-mata mendapatkan imbalan kasih sayang dewa atau dewi.
Dalam prostitusi moderen, kita kenal dengan istilah pelacur, tradisi ini bukan pada budaya spritual, melaikan untuk kebutuhan tertentu. Supratiknya (1995) menyatakan bahwa prostitusi atau pelacur adalah layanan hubungan seks demi imbalan uang.
Berdasarkan penjelasan diatas pelacur itu sebuah praktik penyimpangan demi mendapat kepuasan.
Dalam pengertian yang lain pelacur itu menjajakkan kemolekan tubuhnya dan kecantikkan wajahnya kepada pria-pria hidung belang. Mengumbar setiap jenkal auratnya agar bisa terjual laku.
Tapi itu semua mereka lakukan demi uang, meskipun beberapa melakukannya demi kepuasan dan hobi toh pada akhirnya mereka mendapatkan uang juga. Tak peduli apakah yang dilakukannya adalah zina dan haram, asal dapat uang, apapun jadi.
Bahkan beredar informasi bahwa kini ada yang namanya melacur demi kepopuleran. Menajajakan tubunya, lubang surgawinya, demi kepopuleran, demi menyandang title artis. (A. Zamrud AK, 2014).
Dewasa ini, kata “Prostitusi” (Pelacur) tidak hanya disematkat untuk kaum perempuan semata, hal ini biasa saja terjadi di semua kalangan manusia yang terjeret kepentingan individu dalam mencapai suatu keinginan tertentu, dalam berdemokrasi, orang mengunakan politik sebagai media untuk memenuhi semua kebutuhan yang diinginkan.
Hal ini didasari pada patron kekuasaan yang terdokrin bahwa kekuasaanlah yang mampu memberikan segala-galanya. Politik seakan akan menjadi investasi bagi kalangan tertentu dengan memperkosa prinsip dasar demokrasi bahwa semua yang berasal dari rakyat akan kembali kepada rakyat.
Sejatinya politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia. Robert (1997). Agar bisa melahap sesuap jabatan yang ada dalam parlemen, orang-orang akan dengan berbagai cara melakukan hal dengan sadar menjual diri demi kebutuhannya.
Porne yang artinya menjual diri dalam bahasa Yunani. Istilah Porne sendiri tidak hanya melekat pada diri perempuan pelacur hal ini bisa saja terjadi pada diri setiap manusia, apalagi dalam konteks politik, orang akan rela menjual apa saja termaksud Agama, Idealisme, Suku, Ras dan bahkan diri mereka semata-mata untuk kepentingan tertentu.
Budaya menjual diri dalam tubuh politik sendiri adalah upaya untuk mendapatkan kepercayaan guna menduduki tahta dengan dalil kesejahtraan.
Salah seorang ilmuwan ternama Aristoteles menyatakan bahwa pengertian politik adalah upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Sementara itu menurut Joice Mitchel yang mengatakan bahwa pengertian politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan
kebijaksanaan umum masyarakat seluruhnya.
Robert menyebutkan politik merupakan seni
memerintah dan mengatur masyarakat manusia. Penjelasan dari definisi diatas dapat diambil sebuah pengertian politik merupakan seni atau cara dalam mengambil sebuah keputusan demi kehidupan masyarakat (umum).
Kita akan bertanyaa apakah pelacur politik itu mereka yang digunakan para politisi sebagai bentuk suap yang lain itu? Atau istri-istri simpanan para politisi? Ataukah orang-orang yang melacurkan tubuhnya demi kekuasaan? Tentu saja bukan.
Disini kita bukan membahas tentang oknum-oknum penjaja tubuh itu. Merujuk pada pengertian pelacur diatas, mencari orang lain atau kawan untuk saling memuaskan kemudian mendapatkan uang, begitulah pelacur politik.
Dalam memperoleh sesuatu yang dikehendaki, dalam setiap momentum perta demokrasi terlihat aktor politisi beradu gaya memuja rakyat berdalil sejahtra berkedok agama, idealis, disertai janji janji manis.
Kita akan menyadari betapa buruknya tradisi politik indonesia yang berlandaskan pada gila kekuasaan bermental penjilat. Jika prostitusi ialah praktik menjual diri demi kebutuhannya maka politisi telah banyak berpostitusi.
Hari ini kita saksikan calon politisi yang menjual diri dengan meyakinkan pada masyarakat terkait perubahan dan lain sebagainya.
Apalagi ada yang mencari kawan dan orang lain demi memuaskan hasratnya dan menebalkan isi dompet pribadinya mereka meskipun dengan cara
yang haram sekalipun.
Orang yang mempraktekan hal demikian tidak akan malu untuk datang ke pihak atau partai politik manapun dan menawarkan dirinya agar diusung sebagai calon.
Perilaku seperti ini tak bedanya dengan yang dilakukan oleh Pelacur atau para pekerja Seks Komersial (PSK) yang mana mereka menawarkan semua orang untuk ditiduri demi melampiaskan keinginanya.
Akan jauh lebih bahaya lagi jika mereka dengan kapasitas yang lemah, kemampuan yang terbatas, pengetahuan serta pengalaman yang tidak ada namun diberikan kepercayaan oleh parai untuk ikut bertarung sebagai anggota dewan, pejabat kabupaten, provinsi bahkan pemerintahan nasional sekalipun, terjadi krisis kepemimpinan.
Dengan demikian, fungsi politik tidak berjalan sesuai koridornya. Para pejabat publik, kepala daerah dan anggota dewan tidak akan berpikir tentang kemaslahatan ummat, melainkan permasalahan individu.
Hal ini akan megakibatkan banyak pemimpin yang seharusnya menjadi panutan justru terlibat dalam kasus korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan.
Hal ini memengaruhi kepercayaan publik dan menciptakan budaya skeptisisme di masyarakat.
Selain itu hal ini akan bermuara pada Politik Identitas yang Mendominasi. Fenomena politik
identitas akan sering dimanfaatkan oleh elite untuk meraih kekuasaan.
Alih-alih memperjuangkan kepentingan rakyat, banyak pemimpin justru menggunakan isu-isu SARA sebagai alat politik, menciptakan perpecahan di masyarakat.
Akibatnya, masyarakat kehilangan figur pemersatu yang mampu mengatasi perbedaan. Hal ini disebabkan oleh kepentingan golongan. Saat ini juga banyak pemimpin terjebak dalam kepentingan golongan atau partai politik, sehingga melupakan tanggung jawab mereka untuk melayani rakyat.
Program-program pembangunan sering kali terhambat karena prioritas diarahkan untuk keuntungan politik jangka pendek. Partai politik sejak awal tidak dibebani beban moral, seharusnya dalam setiap kontestasi politik, partai politik mampu memberikan figur terbaik untuk menentukan nasib bangsa.
Indonesia masih kurang memberikan perhatian pada pendidikan kepemimpinan berbasis nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Sistem pendidikan lebih banyak fokus pada penguasaan materi akademik tanpa menanamkan semangat kepemimpinan sejati.
Akibatnya, calon pemimpin masa depan tidak memiliki dasar yang cukup untuk menjadi pemimpin yang berintegritas. Ini juga terjadi didalam tubuh partai politik.
Olehnya penulis mengajak agar mendorong penerapan Pendidikan kepemimpinan harus
ditanamkan sejak dini. Kurikulum sekolah dan perguruan tinggi perlu menyertakan pembelajaran
tentang integritas, etika, dan tanggung jawab sosial.
Program pelatihan kepemimpinan untuk
birokrat, politisi, dan pemimpin masyarakat juga harus diperkuat. Pendidikan ini tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral yang kokoh untuk masa depan Indonesia.
Tinggalkan komentar
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi ditandai *
Top Story
Ikuti kami